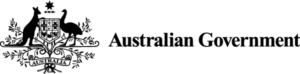Unpaid Care Work: Kerja-Kerja Tersamar Perempuan yang Tak Diakui
Oleh: Fadilla Putri
Awal tahun 2020 lalu, tepat satu bulan sebelum pandemi, saya mengisi sebuah seminar berjudul Research Network Workshop yang diselenggarakan oleh Australia National University (ANU). Acara ini bertujuan untuk saling berbagi hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah akademisi, peneliti, aktivis, hingga lembaga non-profit seperti Rumah KitaB. Di sana, saya berbagi pengalaman penelitian Rumah KitaB dan berada dalam satu panel bersama tiga narasumber lainnya, yaitu SMERU Institut, Naima Thalib (mahasiswa ANU), dan Mia Siscawati (Dosen Kajian Gender Universitas Indonesia). Salah satu hasil penelitian yang menarik perhatian saya adalah penelitian SMERU Institut tentang unpaid care work (UCW).
Dalam definisi yang disampaikan SMERU berdasasarkan berbagai sumber[1], unpaid care work mencakupi mengurus anggota keluarga (direct caring), pekerjaan rumah tangga (indirect caring), dan kerja-kerja komunitas (voluntarily doing care). Berdasarkan data Susenas 2014 sebagaimana diolah SMERU, 97% perempuan/istri melakukan unpaid care work, terlepas ia memiliki pekerjaan penuh waktu, dibandingkan laki-laki/suami yang hanya 25% yang melakukannya. Selain istri, perempuan-perempuan yang melakukan UCW di antaranya adalah menantu perempuan (95%), perempuan kepala keluarga (88%), dan ibu mertua (69%).
Dengan data dan penelitian yang menggunakan perspektif feminis, kita bisa melihat bahwa kerja yang dilakukan perempuan jauh lebih berat daripada laki-laki dengan kerja-kerja rangkapnya yang “invisible” (tersamar) dan tidak berbayar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) diukur berdasarkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Ini artinya, TPAK masih belum merekognisi kerja-kerja perempuan di luar pekerjaannya yang secara langsung berkontribusi secara ekonomi. Namun, apakah benar UCW yang dilakukan perempuan tidak memiliki kontribusi terhadap ekonomi?
Saya teringat rekan-rekan perempuan dari Lombok Utara, tepatnya di Kecamatan Tanjung. Mereka merupakan relawan pengajar di PAUD Alam Anak Negeri. Sekolah ini merupakan sayap gerakan Klub Baca Perempuan, yang merupakan mitra Rumah KitaB. Saya sebut mereka relawan karena meskipun mereka tenaga pengajar, hal itu dilakukan secara sukarela. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mendedikasikan dirinya untuk pendidikan anak usia dini; Sapminten, Atun, Wahyuni, Sofi, dan Rizka.
Kak Atun merupakan salah seorang pengajar di PAUD Alam Anak Negeri. Dengan lokasi rumahnya yang jauh berada di atas bukit, setiap hari ia harus naik turun bukit menggunakan sepeda motor untuk mengajar. Meskipun di tengah wabah Covid-19 sekolah tidak masuk setiap hari, Kak Atun tetap melakukan kunjungan ke rumah-rumah murid untuk memantau proses belajar dari rumah. Sepanjang pengabdiannya, ia mendapatkan ongkos pengganti bensin yang tidak seberapa, dan honor guru yang datang tak menentu.
Sebenarnya, sekolah ini bukan tidak ingin menghargai jerih payah para guru PAUD. Namun dengan segala keterbatasannya, PAUD Alam Anak Negeri belum mampu membayar jerih payah guru-gurunya secara layak. PAUD ini sejak awal dirancang inklusif, sehingga anak murid yang berasal dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sebagian besar dari mereka berayah ibu buruh tani, nelayan, atau mantan TKW; penghasilan mereka yang tergantung musim membuat mereka kesulitan untuk membayar biaya sekolah. Alhasil, pihak sekolah pun tidak mematok jumlah sumbangan pendidikan; yang terpenting anak-anak tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Sebagai gantinya, para orangtua diminta berkomitmen untuk turut belajar dan menyekolahkan anaknya hingga lulus.


Kebetulan Klub Baca Perempuan memiliki kebun pangan, sebuah inisiasi untuk ketahanan pangan di tengah wabah Covid-19. Kebun pangan ini kemudian menjadi kurikulum wajib bagi anak-anak PAUD; mereka belajar menanam hingga memahami dari mana makanan yang mereka konsumsi berasal. Bagi para orangtua murid, mereka juga disiapkan kebun pangan khusus, sehingga para orangtua bisa mengisi waktu sembari menunggu anaknya sekolah. Hasil kebun pangan dapat secara gratis dipanen dan dikonsumsi para murid dan orangtua PAUD. Hasil panen kebun pangan juga dimanfaatkan untuk menambah kas PAUD untuk biaya operasional.
Ketika uang kas sekolah berlebih, Kak Atun dan kawan-kawan bisa mendapatkan honor guru, dan kesemuanya selalu dibagi rata berlima. Namun dibandingkan membayar honor atau pengganti transport, mereka lebih senang membelanjakan uang kas untuk membeli bahan-bahan makanan, untuk kemudian mereka jual kembali. Hasilnya mereka kembalikan ke dana kas sekolah untuk membeli perlengkapan belajar.
Jangan bayangkan hidup Kak Atun dan rekan-rekan pengajar penuh dengan latar belakang ekonomi yang bekecukupan. Namun, mereka tidak pernah mengeluh. Bahkan, saat Nursyida, salah satu penggerak PAUD berencana ingin menutup sekolah karena tak ada biaya untuk menggaji guru, mereka berlima-lah (Kak Atun, Sapminten, Rizka, Sofi, dan Wahyuni) yang paling bersikeras menolaknya. Nursyida menceritakan pada saya, “Dengan kemampuan mereka, bisa saja mereka mencari pekerjaan di luar yang bisa memastikan mereka mendapatkan uang, tapi tidak, mereka tetap bertahan karena mereka mencintai apa yang mereka kerjakan.”
Dari cerita lima perempuan di atas, secara kasat mata, tampaknya kerja mereka tidak secara langsung berdampak pada perekonomian. Namun dengan perspektif feminis, kita bisa melihat bahwa mereka mengisi ruang-ruang kosong di komunitas; pemberdayaan dan pendidikan bagi kelompok marjinal. Mereka mendedikasikan ilmu, pikiran, tenaga, waktu, hingga terkadang uang, ada atau tidak ada upah yang dibayar (sebanding) dengan usaha mereka. Dalam jangka panjang, kerja-kerja mereka memiliki kontribusi besar tidak hanya kepada ekonomi, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama pada anak-anak untuk memaksimalkan potensinya melalu pendidikan, dan menciptakan generasi yang berdaya dan berkualitas.
Mungkin kerja-kerja mereka berlangsung sunyi dan tidak bermakna secara statistik, namun kerja-kerja ini telah memberdayakan setiap orang yang telah mereka rangkul. Namun, mau sampai kapan kerja-kerja semacam ini tidak diakui? Sebab tanpa rekognisi, kerja mereka pun tidak akan dikenali dalam kebijakan.
[1] Budlender & Lund 2008; OECD 2014; UN Human Rights Council 2013
—
Penulis merupakan staf Rumah KitaB dan tulisan ini pertama kali dipublikasikan di sini.

 Photo by
Photo by