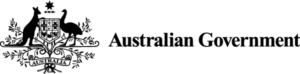Perempuan Santri adalah Perempuan yang Bekerja (Ibuku Perempuan Kepala Keluarga)
Oleh: Jamaluddin Mohammad
Saya hidup dan besar di lingkungan pondok pesantren. Ayah saya seorang guru ngaji sekaligus pimpinan pesantren. Sebelum menjadi PNS, ayah saya sepenuhnya menjadi pengasuh para santri. Sebagai guru ngaji yang tak berpenghasilan tetap, ayah saya pernah nyambi mencari nafkah macam-macam usaha; berjualan bakso keliling, berkebun, hingga berternak ayam.
Untuk mencukupi perekonomian keluarga, ibu saya membuka warung nasi untuk para santri. Ibu pernah bercerita, setiap jam dua malam ia pergi ke pasar belanja keperluan warung sekaligus dilanjutkan untu memasak, menyiapkan sarapan untuk para santri. Setelah beranjak tua dan memiliki enam orang anak, segala urusan warung diserahkan kepada para santri putri senior yang berhidmat kepada pesantren ayah saya. Mereklah yang kemudian mengelolanya.
Ibu saya tipikal perempuan tangguh yang tak mau bergentung pada suami. Untuk menutupi kebutuhan keluarga, ibu saya berdagang, berkebun juga bertani. Seingat saya, selama saya sekolah dan mesantren, saya selalu meminta uang kepada ibu. Jarang sekali meminta kepada ayah. Menurut pengakuan ibu, ia jarang diberi uang oleh ayah. Tapi ibu memaklumi. Hari-hari ayahku dihabiskan seluruhnya untuk mengajar — dari pagi hingga larut malam nyaris tanpa libur. Ia hanya mengandalkan gaji bulanan PNS guru madrasah yang tak seberapa. Ayah saya dimasukkan PNS oleh paman saya yang ketika itu —- sekitar tahun 70an — pemerintah sedang membutuhkan guru agama.
Dalam kehidupan keluarga, ibu saya praktis berperan sebagai kelapa keluarga. Hampir seluruh tanggung jawab dan kebutuhan keluarga ditangani oleh ibu dan cara ibu. Secara de facto ibulah kepala keluarga di rumah tangga orang tua saya. Semua persoalan keluarga dipikirkan dan kemudian diputuskan oleh ibu setelah dibicarakan dengan ayah. Ayah biasanya hanya mengamini dan menyetujui. Meskipun demikian, ayah saya tak pernah menunjukkan bahwa beliau merasa dilangkahi atau diambil alih wewenangnya sebagai “kepala keluarga”. Mungkin, secara normatif, ayah saya adalah kepala keluarga. Namun, seluruh tugas dan fungsi kepala keluarga, wewenangnya ada pada ibu saya.
Mungkin, bagi sebagian orang yang cara pandang keagamaannya masih sederhana, perempuan sebagai kepala keluarga masih dianggap aneh, di luar mainstream, bahkan bertentangan dengan norma dan ajaran agama. Pandangan dan pemahaman bahwa suami sebagai kepala keluarga memang sudah melembaga baik dalam Undang Undang Negara maupun agama. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 31 Ayat 3 menyebut bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Begitu pun dalam agama, mayoritas ulama menafsiri QS An-Nisa:34 dengan laki-laki sebagai kepala keluarga.
Sebagai kepala keluarga, suami memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh terhadap keluarga, termasuk di dalamnya tanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi keluarga. Dari sini kemudian lahir pembagian peran dan tugas berdasarkan jender. Suami bekerja di luar (ruang publik) sedangkan istri mengurus rumah tangga (ruang domestik). Pembagian peran dan tugas ini seolah-olah sesuatu yang given alias sudah paten dan tak bisa diganggu gugat. Bahkan ia disebut sebagai prototype keluarga ideal dan idaman.
Padahal, realitasnya tak sesederhana itu. Dalam struktur masyarakat yang masih bersahaja, boleh jadi pembagian kerja yang biner tersebut tak bermasalah. Beban dan tugas keluarga masih bisa ditanggung dan dipikul semuanya oleh seorang suami. Namun, dalam struktur masyarakat dan susunan pembagian kerja yang kompleks, membangun keluarga tak cukup hanya mengandalkan suami. Sebuah keluarga butuh kerjasama suami-istri secara timbal balik, saling mengisi dan memenuhi fungsi dan tugas masing-masing yang kadang-kadang harus bersilangan untuk membangun kesalingan. Karena itu, pembagian kerja berdasarkan jender antara domestik dan publik sulit menemukan relevansinya lagi. Mengingat kedua ruang tersebut saat ini siapapun bisa saling mengisi dan bertukar tempat.
Demikian halnya yang dilakukan ibu saya. Ketika semua waktu suaminya dihabiskan untuk mengajar dan mendidik santri-santrinya, maka ruang kosong lain diisi ibu saya. Ibu berdagang dan bertani untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga sekaligus membantu para santri yang bagi ibu saya juga dianggap anak-anaknya. Anehnya, hal ini terjadi di sebuah keluarga santri, keluarga yang sangat ketat menjaga norma-norma dan ajaran agama. Sebuah keluarga kiai yang pasti membaca QS An-Nisa:34 itu. Artinya, dalam kehidupan nyata, tafsir keagamaan begitu lentur dan fleksibel, bisa beradaptasi dengan ruang dan waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih: “al-hukmu yadurru ma’a illatihi wujudan awa adaman” (keberadaan hukum bergantung pada ada/tidaknya illat [alasan yang mendasari hukum]). Jika ilat itu berubah, maka hukum pun ikut berubah dan menyeseuaikan diri.
Karena itu, pemahaman dan penafsiran QS An-Nisa: 34 harus dilihat menggunakan kaca mata kesetaraan dan keadilan. Ayat tersebut tidak sedang mensubordinasi perempuan. Jika ayat itu dipahami secara tidak adil dan bias jender, maka akan bertentangan dengan ayat-ayat lain yang mengabarkan dan mengajarkan kesetaraan. Ajaran Tuhan tak mungkin kontradiktif dan saling menegasikan. Sebagaimana disebut dalam QS al-Imran: 195, QS al-Nahl: 97, juga QS An-Nisa 123 yang menyebut bahwa seluruh amal perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Ampunan Allah SWT berlaku sama baik untuk laki-laki maupun perempuan (QS Al-Ahzab: 23-24). Allah SWT juga tak membeda-bedakan jenis kelamin kecuali berdasarkan ketakwaan (QS al-Hujurat: 13).
Stereotype Perempuan
Hasil penelitian Rumah KitaB tentang “Perempuan Bekerja di Ruang Publik” menunjukkan ada semacam trend baru di kalangan muslim perkotaan untuk merumahkan perempuan. Mereka ingin menghidupkan lagi nilai-nilai dan ajaran konservatif yang membatasi aktivitas dan pekerjaan perempuan hanya di dalam rumah. Salah satunya berangkat dari pandangan stereotype bahwa perempuan adalah aurat dan sumber fitnah. Karena itu, bukan hanya tubuhnya yang harus ditutup rapat-rapat, ruang hidupnya pun harus dibatasi. Salah satu alasan kenapa perempuan tak dibolehkan keluar atau bekerja di luar rumah adalah karena alasan ini. Hal ini didukung pula oleh penafsiran dari ayat “Berdiam dirilah di dalam rumah dan jangan menampakkan perhiasan (aurat) di hadapan orang lain (QS al-Ahzab: 33).
Jika melihat asbab nuzul (konteks) ayat ini, seseungguhnya bukan perintah untuk mendomestikasi perempuan. Ayat ini menyuruh istri-istri Nabi SAW untuk bersikap dan berprilaku sederhana sekaligus memperbanyak ibadah. Namun, mengapa ayat ini dipukul rata untuk semua perempuan? Hal ini tak lain dan tak bukan karena berangkat dari steretoype bahwa perempuan adalah aurat, sumber fitnah, karena itu fitrahnya di dalam rumah.
Jika kita jujur membaca ayat-ayat tentang aurat dan perintah menundukkan pandangan (ghaddul bashar), sesungguhnya tak hanya berlaku bagi perempuan (QS An-Nur: 31), melainkan berlaku juga bagi laki-laki (QS An-Nur: 30). Artinya, kita harus jujur dan proporsional, jika perempuan dianggap sebagai seumber fitnah karena aurat, harusnya laki-laki pun demikian karena sama-sama memiliki aurat. Namun, kenapa hanya perempuan yang disebut suber fitnah? Di sinilah pentingnya bersikap adil sejak dalam pikiran, dengan membaca ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Wallahu a’lam bi sawab.
—
Penulis merupakan peneliti Rumah KitaB dan tulisan ini pertama kali dipublikasikan di sini.

 Photo by
Photo by