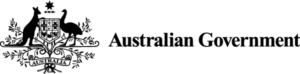Hari Ibu dan Keadilan Jender di Ruang Publik
Oleh: Lies Marcoes
Di antara sejumlah isu terkait perempuan, peringatan Hari Ibu, 22 Desember, ditandai oleh makin menguatnya ujaran konservativisme agama yang menghambat perempuan masuk ke ruang publik.
Awal Desember, dalam pilkada serentak di seluruh Indonesia, perempuan dimungkinkan secara politik jadi calon. Namun di sepanjang kampanye pula ujaran yang menolak kepemimpinan perempuan terus mengemuka. Ungkapan yang menyoal kehadiran perempuan di ruang publik muncul makin nyaring. Ini mengherankan bagi Islam Indonesia.
Pertama, Islam Indonesia adalah Islam moderat yang memberi tempat luas bagi perempuan berkiprah di ruang publik. Kedua, perjuangan kebebasan perempuan telah berlangsung hampir satu abad, sejak kaum pergerakan perempuan menyuarakan tuntutan kebebasan sebagai platform gerakan politik mereka di 1928.
Dalam pergerakan itu ormas Islam Aisyiyah telah ambil bagian. Namun kini, ajakan bagi perempuan untuk balik ke rumah dengan alasan ruang publik bukanlah ruang bagi perempuan muncul hampir satu abad kemudian. Apa gerangan yang tengah terjadi pada perempuan di negeri ini?
Sepanjang 2020, Rumah Kitab menyelenggarakan penelitian tentang dampak fundamentalisme pada kekerasan berbasis jender. Penelitian yang dilakukan di Solo, Jakarta, Bandung, Bekasi dan Depok ini mengeksplorasi elemen keamanan insani pada perempuan yang digali dari pengalaman perempuan dalam hubungannya dengan pandangan keagamaan sebagai elemen penting dalam mengonstruksikan jender.
Melalui riset etnografi feminis ini diperoleh temuan-temuan baru yang dapat digunakan sebagai bahan advokasi penanggulangan kekerasan ekstrem di Indonesia. Temuan mengkristal pada tiga konsep.
Pertama, perempuan secara alamiah dianggap sebagai fitnah (ujian bagi laki-laki, godaan, penyebab kekacauan); karenanya, kedua, fitrah perempuan adalah tunduk secara permanen pada laki-laki sebagai upaya mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh fitnah perempuan.
Kedua konsep itu (fitnah dan fitrah) menjadi landasan dari rumusan tentang konsep jender transendental, yaitu sebuah ide tentang keadilan bagi perempuan yang hanya bisa dicapai ketika syariat Islam telah diterapkan atau negara Islam telah terbentuk atau bahkan dijemput kelak di akhirat.
Antitesis keadilan jender
Ketiga konsep ini jadi antitesis atas konsep keadilan jender yang selama ini dikembangkan sebagai metode dan strategi untuk meraih keadilan bagi perempuan melalui kesetaraan jender dalam pembangunan. Sebaliknya, konsep fundamentalis tentang perempuan itu menjelaskan narasi dan logika kekerasan berbasis jender pada perempuan dengan cara merampas keamanan insani mereka, terutama di ruang publik.
Kekerasan dilakukan melalui hegemoni paham fundamentalisme lewat proses penundukan yang berlangsung terus-menerus setiap hari dalam kegiatan pengajian, TV, radio, medsos.
Penelitian ini juga mengoreksi konsep “kekerasan ekstrem” yang selama ini didefinisikan secara maskulin sebagai kekerasan yang mengancam nyawa manusia dalam bentuk kekerasan fisik menggunakan media penghancur, seperti bom atau senjata lain.
Penelitian oleh 14 peneliti terlatih itu membuktikan , hegemoni ajaran fundamentalisme adalah bentuk lain dari kekerasan ekstrem yang bisa melumpuhkan kewarasan berpikir terkait hidup dan kehidupan perempuan.
Kekerasan itu mengancam jiwa dan pikiran perempuan untuk terbebas dari rasa takut, rasa bersalah, rasa tak berdaya yang menciptakan ketergantungan penuh kepada pihak lain (laki-laki, maskulinitas, patriarki). Ancaman-ancaman itu bersumber dari ajaran yang memosisikan perempuan sebagai pendosa, sumber fitnah, ahli neraka, yang terus-menerus disuarakan untuk menuntut kesalehan perempuan.
Di berbagai platform medsos mereka, hampir tiap hari ditemukan ujaran kebencian berbasis pandangan keagamaan yang merendahkan perempuan. Itu bisa dibaca di Twitter, Facebook, dan Instragram. Cuitan seorang ustadz misalnya berbunyi “ Wanita itu, diam aja jadi fitnah, apalagi gerak”.
Seorang pengisi pengajian di mal di Jakarta berteriak “ Mau dari sisi manapun, mau menghadap ke manapun perempuan itu ahli neraka, suaranya, rambutnya, mukanya, hiasannya, pakaiannya semua dapat menjadi suluh api neraka”.
Di Facebook, grup Muslimah yang secara terbuka menyebut diri kelompok Salafi menghukum sesama Muslimah yang aktif di luar rumah. Menurut mereka para perempuan itu telah membiarkan rumah tangganya menjadi “the house of titanic”. Mereka menghukum perempuan serupa ini ibu yang gagal dalam pendidikan anak-anak perempuannya jadi calon ibu dan pengurus rumah tangga.
Dalam Instagram dengan gambar-gambar perempuan bertoga diingatkan ”Perempuan boleh kok bekerja asal: mendapat izin wali, berpakaian sesuai syariat, aman dari fitnah, ditemani muhrim saat bepergian dinas”. Juga disertakan diagram yang menggambarkan hal-hal yang membuat perempuan sebagai pengumpul dosa: bersolek, tatapan mata, bercampur dengan lelaki bukan muhrim, jabat tangan, suara, aurat. Instagram itu ditutup dengan ajakan: “Ukhti kembalilah ke rumah!”. “Ukhti berusahalah sekuatnya untuk menghindari fitnah di luar rumah”.
Bagi umat Islam Indonesia, ajakan serupa itu sungguh aneh dan utopis. Bahkan dalam relief Borobudur yang merupakan potret realitas kehidupan penduduk di Jawa abad ke-9, perempuan sudah tampil di lapangan pekerjaan apapun. Mayoritas keluarga Muslim di Indonesia anak petani dan pedagang. Dalam keluarga-keluarga Muslim lelaki dan perempuan sama-sama bekerja.
Berkat pendidikan, ragam peluang bagi perempuan untuk bekerja terbuka luas. Mereka bisa mengerjakan apa saja yang lelaki kerjakan apalagi pekerjaan yang dianggap perpanjangan tugas mereka di rumah. Melampaui keterbatasan peran tradisionalnya, mereka bekerja di sektor apapun sesuai pendidikan, peluang dan kepintarannya.
Ungkapan yang menolak atau meminta perempuan tinggal di rumah, bukanlah datang dari manusia gua atau negara yang membatasi perempuan di ruang publik. Nama-nama mereka sangat Indonesia atau nama Arab Indonesia. Itu artinya mereka pastilah datang dari keluarga yang ayah ibunya, atau ayahnya, atau ibunya bekerja untuk menyekolahkan mereka.
Orangtua mereka tentu berharap anak perempuan yang mereka biayai pendidikannya itu akan mengamalkan ilmunya, dan dapat pekerjaan serta mampu mandiri secara ekonomi. Racun ajaran apa yang membuat mereka seperti itu?
Tentu argumen itu dengan mudah bisa dipatahkan. Memang semua lelaki sanggup jadi pencari nafkah? Memang semua perempuan berpasangan sehingga bisa mengharap curahan nafkah seumur hidup? Bagaimana dengan perempuan lajang?
Tapi dalil mereka bahwa ruang publik itu tak aman bagi perempuan, sebetulnya tak sepenuhnya salah. Tempat di mana perempuan bekerja rentan pelecehan verbal atau fisik; perempuan diupah lebih rendah, jadi sasaran eksploitasi.
Singkatnya, perempuan masih mengalami dehumanisasi di ruang publik. Dan ini jadi santapan mereka untuk membenarkan argumentasinya. Karenanya tak sedikit perempuan terdidik sekalipun gamang dengan kehadiran mereka di ruang publik.
Sikap ormas keagamaan
Alih-alih menuntut tempat kerja yang aman, nyaman dan ramah bagi perempuan dengan dasar argumen agama bahwa bekerja adalah hak dan fitrah, para penganjur perempuan balik ke rumah malah menuntut perempuan untuk menutup diri, baik fisik atau simbolik guna mengatasi kejahatan di ruang publik. Sambil berpegang pada teks secara tekstualis, mereka bersikeras tempat perempuan terbaik adalah di rumah.
Dengan demikian secara eksplisit mereka mengakui, ruang publik sebagai sasana adu kuat bagi para lelaki. Asumsi paralel dari anggapan itu rumah adalah surga. Seolah mereka tak pernah bertemu dengan perempuan korban kekerasan. Padahal Komnas Perempuan setiap tahun mengeluarkan catatan bahwa kekerasan seksual paling banyak terjadi di rumah dan dilakukan oleh orang terdekat oleh anggota keluarga sendiri.
Sepertinya para penganjur perempuan balik ke rumah itu tak pernah baca nasib anak perempuan seperti Malala dan perempuan lain di negerinya yang diusir dari ruang pendidikan, ruang peradaban, atas nama (ideologi) Islamisme.
Mereka membunyikan alarm yang memaksa perempuan balik ke rumah, namun juga alarm yang mengancam perempuan di ruang publik. Dan bunyi alarm itu terasa kian nyaring karena hampir tak ada respons atas fenomena ini dari organisasi keagamaan moderat di Indonesia baik NU atau Muhammadiyah. Padahal keduanya dapat berkembang berkat sayap organisasi perempuan mereka.
—
Penulis merupakan Direktur Rumah KitaB dan artikel ini pertama kali dipublikasikan oleh Kompas.