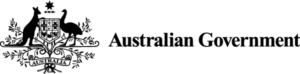Benarkah Perempuan itu Aurat, sehingga seorang Muslimah sebaiknya tidak Bekerja?
Oleh: Dr. Faqihuddin Abdul Kodir
Pertanyaan ini sering disampaikan berbagai pihak, terutama dalam mimbar-mimbar pengajian, bahkan obrolan warung-warung makan. Perempuan dianggap berpotensi menggoda laki-laki, atau digoda laki-laki, sehingga sebaiknya tidak berada di ruang publik. Seperi bekerja misalnya. Hal ini sebagai tindakan preventif agar pesona tubuhnya, yang bisa menggoda, atau kemungkinan diganggu dan digoda, tidak membahayakan dirinya dan orang lain.
Demikianlah narasi keagamaan yang berbasis fitnah tubuh perempuan. Termasuk narasi aurat perempuan yang bekerja. Sesungguhnya, tidak hanya untuk isu bekerja, tetapi semua aktivitas apapun yang dilakukan perempuan di ruang publik. Bahkan bisa saja perilaku-perilakunya di dalam ruang domestik bersama keluarga. Dan pada akhirnya, semua hukum atau etika yang menyangkut perempuan akan dirumuskan hanya sebatas cara pandang tubuhnya semata: menggodakah (subyek)? Atau akan digodakah (obyek)?
Padahal, hukum Islam memiliki rumusan kerangka Maqashid Syari’ah. Yaitu, kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Termasuk kehidupan perempuan. Jika kita meyakini perempuan sebagai manusia, dan menjadi subyek yang disapa Islam, maka ia juga harus memperoleh kemaslahatan yang dituju Islam. Baik yang terkait agamanya (hifz ad-din), akal budinya (hifz al-‘aql), jiwanya (hifz an-nafs), hartanya (hifz al-mal), dan keluarganya (hifz an-nasl).
Dengan demikian, narasi perempuan adalah aurat, dalam isu bekerja maupun yang lain, harus dipastikan tidak melanggar kerangka dasar dari Maqashid Syari’ah ini. Karena perempuan sebagai manusia yang menjadi subjek utuh kehidupan, tidak hanya memiliki tubuh, tetapi juga jiwa, akal budi, relasi dan tanggung-jawab sosial, dan berbagai hak dan tanggung-jawab yang lain.
Aurat sebagai Titik Lemah Seseorang
Jika merujuk pada al-Qur’an (al-Ahzab, 33: 13), aurat adalah sesuatu yang mudah diserang musuh suatu kaum atau bangsa dan dijadikan alat untuk menghancurkan keseluruhan kaum atau bangsa tersebut. Agar tidak lagi menjadi aurat, sesuatu harus diperkuat, dilindungi, atau bahkan diubah menjadi alat pertahanan yang justru meningkatkan harga diri dan wibawa suatu kaum dan menakutkan musuh-musuh mereka.
Rumah dan keluarga yang berada di daerah pinggir perbatasan suatu kaum, pada zaman perkabilahan dahulu, ketika sedang kontak perang, dianggap sebagai aurat. Yaitu sesuatu yang mudah terancam dikuasi musuh, dihancurkan, atau digunakan sebagai jalan untuk menghancurkan seluruh kaum. Rumah yang aurat diperlukan perlindungan dan penguatan. Tetapi ketika rumah dan keluarga tersebut menjadi kuat, atau terlindungi secara baik, atau taktik perang sudah tidak lagi menyerang perbatasan tetapi langsung ke jantung kota-kota utama, maka rumah dan keluarga di pinggiran perbatasan tidak lagi dianggap sebagai aurat. Sebaliknya rumah-rumah yang tidak terlindungi di tengah kota bisa berubah menjadi aurat, atau sasaran empuk pelemahan dan penghancuran oleh pihak musuh.
Perempuan, dalam suatu hadits (Sunan Turmudzi, no. 1206) dianggap aurat, sebaiknya dipahami dalam konteks makna ayat tersebut di atas, bukan sekedar aurat fisik badaniyah yang seksual, melainkan lebih utuh secara sosial. Sehingga, perempuan dianggap aurat ketika mereka lemah, bodoh, mudah diperdaya, mudah dijadikan alat oleh individu atau pihak-pihak tertentu untuk memperdaya dan menghancurkan masyarakat secara umum. Tetapi ketika mereka justru menjadi kuat, pintar, mandiri, bijak, dan paham situasi, sehingga tidak lagi mudah diperdaya, mereka bukan lagi aurat.
Sebaliknya, laki-laki yang lemah, bodoh, mudah diperdaya, dan mudah dijadikan alat oleh individu-individu atau pihak-pihak tertentu untuk memperdaya dan menghancurkan masyarakat secara umum, adalah juga aurat. Seperti anak-anak yang lemah, atau laki-laki yang sudah uzur, dalam konteks situasi perang, seringa dianggap sebagai aurat.
Perempuan yang lemah dan dianggap aurat perlu penguatan, begitupun laki-laki lemah yang dianggap aurat juga perlu pemberdayaan. Tidak semua laki-laki kuat dan mampu melindungi, sebagaimana tidak semua perempuan lemah dan perlu perlindungan. Siapapun bisa menjadi aurat dan perlu perlindungan, laki-laki maupun perempuan. Begitupun, siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kapasitasnya masing-masing bisa mejadi pelindung, penguat, dan pemberdaya mereka yang lemah.
Aurat sebagai Sesuatu yang Mendorong pada Keburukan
Kita juga sering mendengar bahwa suara perempuan adalah aurat. Karena itu, perempuan dilarang bekerja dalam hal-hal yang mengekspose suaranya ke publik. Sesungguhnya suara perempuan, dalam suatu pandangan fiqh tertentu, dianggap aurat adalah ketika suara itu mendorong atau mengajak pada tindakan-tindakan asusila, yang membuat seseorang berada pada titik lemahnya secara spiritual dan sosial. Jika tidak, yang tentu saja bukan aurat. Ini untuk menerima preseden banyak perempuan pada masa Nabi Saw bersuara, berdakwah, belajar, bertanya, dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada keluarga, kolega, dan masyarakat.
Dengan makna yang demikian, secara mubadalah, suara laki-laki yang juga mendorong, mengajak, atau bahkan merayu dan mengkondisikan tindakan asusila adalah juga aurat. Jika laki-laki secara umum tidak dilarang bersuara, sekalipun ada dari mereka yang mendorong dan mengajak tindakan asusila, maka perempuan juga seharusnya tidak diharamkan suara mereka, hanya karena beberapa individu dari mereka yang dianggap menggoda dan memesona. Yang diperlukan, satu sama lain, laki-laki dan perempuan, tidak menggunakan suara mereka untuk menggoda dan menjerumuskan.
Lebih jauh lagi, bisa saja setiap suara yang mendorong pada tindakan-tindakan haram, seperti zina, kebencian, konflik, kekerasan, dan korupsi, adalah juga dianggap aurat yang harusnya diwaspadai. Baik suara itu keluar dari laki-laki maupun perempuan. Pada saat yang sama, masing-masing, laki-laki dan perempuan juga diperintahkan untuk mengubah suara yang aurat ini menjadi suara yang mendorong pada kebaikan, anti korupsi, persatuan, dan perdamaian.
Dengan demikian, misi Islam untuk “amar ma’ruf dan nahi munkar”, yaitu menguatkan daya dorong untuk mewujudkan kebaikan dan menguatkan daya tahan dari segala keburukan, benar-benar menjadi sesuatu yang dikerjakan bersama oleh laki-laki dan perempuan. Persis seperti yang diamanatkan al-Qur’an, Surat at-Taubah (9), ayat ke-71. Sehingga kerahmatan dan kemaslahatan yang diharapkan Islam membumi bagi semua, dilakukan dan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan.
Keberpihakan Islam pada yang Lemah
Makna aurat seperti disebutkan di atas menjadi relevan dengan visi dan misi Islam untuk melindungi yang lemah (mustadh’afin), sekaligus untuk memastikan kehidupan sosial yang terlindungi dari segala kemungkinan buruk yang bisa menimpa siapa saja. Dalam pemaknaan ini, Islam harus memberdayakan siapapun yang memiliki aurat, yang akan melemahkan dirinya, atau menjadi titik lemah dirinya yang bisa diserang oleh orang lain. Sebaliknya, siapapun yang memiliki kapasitas, untuk menutupi aurat seseorang, dengan melakukan kerja-kerja perlindungan dan pemberdayaan, adalah dipanggil oleh Islam untuk berkiprah dan berkarya. Yang memiliki aurat bisa laki-laki, dan bisa perempuan. Yang menutupi aurat juga bisa laki-laki dan bisa perempuan.
Tubuh perempuan bisa menjadi aurat, yaitu menjadi titik lemahnya, karena bisa saja ada laki-laki yang tergoda, lalu berbuat hal-hal buruk padanya. Namun, perlindungannya bukan dengan melarangnya dari aktivitas di luar publik. Tetapi dengan membuat sistem sosial yang membuatnya nyaman, aman, dan terlindungi ketika beraktivitas sosial, karena tindakan buruk laki-laki terhadap dirinya. Di sinilah arti menutup aurat yang relevan dan komprehensif. Ini juga berlaku bagi laki-laki, yang bisa saja menjadi aurat, dan berpotensi diganggu oleh orang lain di ruang publik. Yang harus dilakukan adalah menyediakan ruang publik yang aman dan melindungi siapapun, laki-laki maupun perempuan.
Perempuan tidak bisa dilarang bekerja hanya karena ia dianggap aurat. Karena, aurat sendiri bisa ada pada laki-laki, dan dia juga tidak dilarang dari bekerja. Aurat dalam arti pesona tubuh atau yang lain, dari laki-laki maupun perempuan, harus dijaga bersama agar tidak menimbulkan keburukan, terhadap laki-laki maupun perempuan. Bukan dengan melarang perempuan bekerja. Namun, dengan kesadaran bersama untuk membangun dan mewujudkan sistem pergaulan sosial yang sehat, aman, dan melindungi.
Lebih dari itu, seseorang yang tidak bekerja justru bisa menjadi aurat secara sosial. Dia terancam diperlakukan buruk di ruang domestik maupun publik. Sebaliknya, bekerja atau beraktivitas di ruang publik secara positif, justru bisa menutupi berbagai kelemahan (aurat) seseorang, laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang bekerja justru sedang memperjuangkan agar bisa memiliki bekal untuk menutupi titik lemah hidupnya, yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang tidak memiliki bekal untuk hajat hidupnya, adalah orang yang paling lemah, dan sangat mudah diperdaya, diganggu, bahkan diperlakukan buruk oleh orang lain. Bekerja bisa menutupnya dari aurat hidupanya tersebut. Wallahu a’lam.