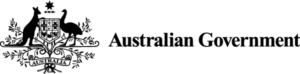Kolom Kang Faqih: Benarkah Muslimah Bekerja Perlu Izin Suaminya?
Oleh: Faqihuddin Abdul Kodir
Jawabanya bisa benar dan bisa tidak, karena hukum selalu melihat konteks, kondisi, dan alasan (al-hukm yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman). Kita mengawali penjelasan pertama, yaitu ketika izin suami menjadi ajang transparansi, diskusi, dan antisipasi, maka ia menjadi baik dan perlu. Seorang perempuan muslimah yang mau bekerja, tentu, memerlukan ruang berbagi informasi, dukungan keluarga terutama suami, penguatan, dan bisa jadi antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Izin suami menjadi ajang bagi perempuan untuk hal-hal baik ini, yang akan menopang dan mendukungnya untuk memperoleh yang terbaik dari keputusannya untuk bekerja.
Bisa jadi, melalui ajang izin ini, suami lebih memahami jenis pekerjaan yang akan digeluti istrinya, mengenal lingkungan pekerjaan tersebut, atau orang-orang untuk jenis pekerjaan yang serupa, atau jaringan dan hal-hal lain yang bisa mendukungnya. Minimal, dengan mengetahui istrinya bekerja di suatu tempat, suami dapat mengantisipasi hal-hal tertentu ke depan. Bisa jadi ditanya anak-anak, orang tua, keluarga, atau kolega tentang keberadaan istrinya. Bisa jadi, ada kejadian pada istrinya yang memerlukan bantuanya. Atau antisipasi apapun, yang memang, dalam kehidupan sering terjadi.
Jika izin bekerja ini benar-benar menjadi ruang seperti demikian, maka hukumnya akan mengikuti hukum bekerja itu sendiri. Jika bekerja itu hukumnya wajib bagi seorang perempuan, misalnya karena dibutuhkan masyarakat dan dia satu-satunya orang yang mampu mengerjakan hal tersebut, atau penghasilanya diperlukan untuk kebutuhan primer keluarga, maka izin suami menjadi wajib. Jika hukum bekerjanya turun menjadi sunnah, maka izinnya juga menjadi sunnah. Hal ini didasarkan pada kaidah, bahwa sesuatu yang baik, wajib maupun sunnah, jika tidak sempurna tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini juga menjadi baik dan perlu (ma la yatimm al-hasanu illa bihi fahuwa hasanun).
Izin suami sebagai ajang informasi, diskusi, dan antisipasi mempersyaratkan relasi pasutri (pasangan suami istri) yang mubadalah (kesalingan). Relasi ini, seperti digariskan Al-Qur’an, memiliki lima pondasi. Yaitu, pertama, relasi pasutri dipandang sebagai kemitraan dan berpasangan (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn, QS. 2: 187); kedua, relasi pasturi dipandang sebagai ikatan kokoh yang harus dijaga bersama (mitsaqan ghalizan, QS. An-Nisa, 4: 21); ketiga, relasi harus bertumpu pada perilaku saling berbuat baik satu sama lain (mu’asyarah bil ma’ruf, QS. An-Nisa, 4: 19); keempat, satu sama lain saling bermusyawarah (tasyawurin, QS al-Baqarah, 2: 233), dan kelima, satu sama lain saling mencari kerelaan (taradhin, QS al-Baqarah, 2: 233).
Dengan lima pondasi relasi mubadalah yang Qur’ani ini, tidak hanya izin suami, melainkan izin istri bagi suami yang akan bekerja juga menjadi baik dan perlu. Fungsinya sama, sebagai ajang informasi, diskusi, dan antisipasi. Saat ini, besar kemungkinan, sang istri memiliki pengetahuan yang cukup yang bisa dibagikan kepada suaminya terkait yang akan dikerjakannya. Minimal, sang istri memiliki informasi, sehingga bisa ikut mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi pada suaminya atau pekerjaanya. Lebih mulia lagi, jika izin istri dijadikan suami sebagai ajang implementasi dari lima pondasi relasi yang Qur’ani di atas. Sebagai perwujudan relasi berpasangan (zawaj), mengokohkan ikatan pernikahan (mitsaqan ghalizan), memperlakukan istri secara baik (mu’asyarah bil ma’ruf), bermusyawarah (tasyawurin), dan mencari kerelaan istri (taradhin).
Hukum izin suami akan berbeda pada kondisi relasi yang timpang, dimana perilaku suami semena-mena dan menggunakannya sebagai ajang hegemoni terhadap istrinya. Istri dilarang bekerja tanpa sebab, dilarang mengaktualisasikan dirinya demi impuls suami yang tidak jelas, dan ditempatkannya sebagai subordinat yang harus selalu minta izin suami dalam segala urusan. Relasi yang demikian bertentangan dengan lima pondasi relasi Qur’ani di atas, sehingga izin suami yang turun dari relasi timpang ini, juga menjadi tidak Qur’ani. Pada kondisi yang demikian, yang diperlukan bukanlah membiasakan izin suami oleh seorang istri, tetapi mengedukasi suami agar terlebih dahulu memiliki relasi yang Qur’ani dengan lima pondasi mubadalah tersebut di atas.
Tanpa prasyarat relasi mubadalah ini, izin suami justru bisa membuat seorang laki-laki bertambah jumawa, sombong, dan semena-mena. Hak-hak dasar yang dimiliki seorang perempuan, untuk hidup nyaman, belajar, bekerja, berpartisipasi secara sosial, bisa dilarang suaminya secara semena-mena melalui tiket ideologi izin yang dimilikinya. Untuk laki-laki seperti ini, seperti pesan Nabi Muhammad Saw, justru ditolong dengan mengendalikannya dan tidak menggunakan praktik izin untuk menzalimi istrinya.
عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ (صحيح البخاري، رقم: 2484).
Dari Anas r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, kami pasti menolong yang dizalimi, bagaimana menolong yang zalim itu? Rasul Saw menjawab: “Menolong yang zalim itu dengan mengendalikannya (agar tidak berbuat zalim lagi)”. (Sahih Bukhari, no. 2484).
Ketika izin suami digunakan untuk menzalimi hak-hak istri sebagai manusia muslimah yang utuh, maka kita diminta Nabi Saw menolong yang dizalimi dan yang menzalimi. Yaitu dengan melarang praktik izin yang zalim dari suami dan mendukung para perempuan yang dizalimi oleh praktik tersebut. Di antaranya adalah dengan mengedukasi laki-laki (suami) dan perempuan (istri) tentang relasi yang mubadalah dan mendorong mereka mempraktikkan lima pondasi Qur’ani tersebut di atas. Hanya dalam relasi yang demikian, praktik izin suami bisa membawa kebaikan dan keberkahan.
Apakah ada teks hadis yang menuntut seorang muslimah yang mau bekerja meminta izin dari suaminya? Tidak ada. Lalu, darimana pandangan yang cukup populer ini berkembang? Dari ajaran dasar bahwa seorang istri harus selalu patuh kepada suami. Padahal kepatuhan dalam Islam, sebagaimana juga ditegaskan Nabi Saw, harus dalam hal-hal yang akan membawa kebaikan, bukan dalam hal-hal yang justru membawa kemaksiatan, atau keburukan dan kemafsadatan (Musnad Ahmad, no. 1110).
Sebaliknya, untuk hal-hal yang secara mendasar adalah baik, Nabi Saw justru melarang laki-laki menggunakan praktik izin ini bagi menghalangi para perempuan dari hak-hak dasar yang mereka miliki sebagai muslimah. Kita bisa merujuk pada pernyataan Nabi Saw di bawah ini:
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا (صحيح البخاري، رقم: 881).
Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, Abdullah bin Umar ra, dari Nabi Saw, bersabda: “Jika istri seseorang di antara kalian sudah meminta izin, maka (izinkan dan) janganlah halang-halangi dia”. (Sahih Bukhari, no. 881).
Teks hadis ini secara gamblang meminta laki-laki untuk tidak menghalangi-halangi istrinya, jika sudah meminta izin. Teks hadis ini bersifat umum untuk hal-hal yang secara mendasar adalah baik, seperti beribadah, belajar, bekerja, beramal sosial, dan yang lain. Beberapa riwayat lain memberi contoh tentang izin untuk pergi ke masjid, terutama salat pada malam hari, dimana para suami biasanya merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak baik, sehingga merasa berhak untuk tidak mengizinkan. Namun, Nabi Saw dengan tegas mengatakan: izinkan dan jangan halangi para perempuan dari masjid-masjid Allah (Sahih Muslim, no. 1019).
Dengan demikian, merujuk pada hadis tersebut dan prinsip-prinsip relasi mubadalah di atas, praktik izin adalah baik di antara pasutri jika diimplementasikan dalam kerangka berbagi informasi di antara mereka, berdiskusi, bermusyawarah, berbagi pengetahuan dan dukungan, sertai antisipasi hal-hal yang justru bisa mendatangkan keburukan bagi kehidupan mereka berdua. Jika tidak dalam kerangka yang demikian, maka praktik izin pasutri perlu ditinjau ulang. Wallahu a’lam.