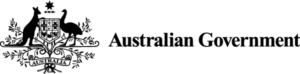Sumbangan Kerja Rumah Tangga
Oleh: Sinta Febrina
Dalam rangka Hari Perempuan Internasional saya ingin menurunkan kembali tulisan saya di Kompas beberapa tahun lalu. Hingga saat ini setelah saya pindah ke Amerika untuk melanjutkan studi master saya dengan memboyong dua anak saya, tulian ini tetap relevan. Tulisan ini mempersoalkan inkonsistensinya penghargaan sosial ekonomi kepada perempuan yang memilih karier sebagai IRT – ibu rumah tangga. Terdapat paradoks, di satu pihak IRT diagungkan, dianggap kunci keberhasilan keluarga; di pihak lain, peran itu tak direkognisi secara konkrit dalam pembangunan, pun dalam analisis ekonomi.
Survei Litbang Kompas menjelang Hari Ibu 2015 menggaris bawahi gambaran itu. Sejumlah 1.640 pelajar Menengah Atas dari 12 kota besar menempatkan Ibu sebagai tokoh penting bagi kehidupan mereka. Sebanyak 47, 1 dari mereka menyebut ibu sebagai tempat curhat dibandingkan ayah, yang hanya mendapat 7,7 persen; lebih dari lima puluh persen responden remaja memilih membangun komunikasi dengan ibu, dibandingkan ayah (kurang dari 10 %). Bahkan mereka memilih kawan melalui ragam media sosial ketimbang dengan ayah. Mereka juga tetap memilih ibu sebagai pahlawan, (46,2%) meskipun mereka menyebut ayah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. (Litbang Kompas 2015)
Namun hasil survei itu seperti tak terhubung dengan kajian politik ekonomi. Sejauh saya tahu, kajian politik ekonomi Indonesia jarang sekali menganalisa peran dan sumbangan IRT atau merekognisi dengan mengkonversikan sumbangan tenaga kerja mereka dalam mengurus rumah tangga, anak, menunjang karier suami dan mengelola komunitas sebagai sumbangan bagi pembangunan.
Bacaan saya mengantarkan kepada jawaban klasik bahwa persoalan ini berpangkal dari pandangan biner soal peran publik-domestik. Pemisahan ini, dalam konteks masyarakat industri melahirkan pembagian kerja gender yang tak setara. Pembagian kerja gender ini menempatkan perempuan dalam kerja reproduksi seperti pengasuhan dan pemeliharaan keluarga yang diberi label Ibu Rumah Tangga, sementara kerja produktif secara otomatis dihubungan kepada lelaki sebagai kepala keluarga, pencari nafkah utama. Meskipun kenyataan itu telah lama berubah dan bergeser, namun label peran dan status yang berangkat dari oposisi biner itu nyaris tak berubah.
Persoalannya, seluruh perhatian politik ekonomi tampaknya hanya meneropong aktivitas manusia di ruang publik dan untuk jenis pekerjaan berbayar. Sementara pekerjaan IRT yang secara normatif dituntut menghasilkan tatanan keluarga yang sehat, aman dan nyaman, tak dibedah oleh pisau analisis ekonomi serupa itu. Sekat biner telah menempatkan IRT di posisi yang sulit diteropong oleh analisis ekonomi yang tersedia.
Adanya pembagian kerja gender juga melahirkan kesenjangan kepada perempuan sebagai IRT. Menjadi IRT pada kenyataannya hanya menghasilkan penghargaan moral sosial atau keagamaan. Sumbangan mereka tak pernah dikalkulasi secara ekonomis. Bandingkan misalnya dengan kerja produktif yang bukan hanya mendapatkan pengakuan, tetapi juga memiliki peluang untuk mengembangkan diri dan membangun kapasitas. Ini karena peran dan kehadirannya direkognisi dalam politik ekonomi dan karenanya kebutuhan-kebutuhannya relatif lebih diperhatikan dan dipenuhi. Pembagian kerja gender bukan hanya melahirkan kesenjangan tetapi juga tak ada peluang yang setara (equal oportunity).
Lihat saja, banyak pasangan yang semula memasuki Rumah Tangga secara setara kelak memunculkan ketimpangan ketika salah satu memilih tinggal di rumah demi keluarga. Banyak pasangan yang sama-sama lulusan perguruan tinggi, secara sadar melakukan pembagian kerja demi survival mereka. Namun pada akhirnya mereka menghadapi situasi yang menempatkan salah satu pihak jadi subordinat dan stagnan. Suami dapat melanjutkan sekolah, mengembangkan karier dan mencari nafkah, sementara istri menjadi IRT dan hilang dari radar analisis. Ini karena oposisi biner juga bersifat diskriminatif. Ruang publik senantiasa menyediakan segala macam pilihan bagi mereka yang aktif didalamnya untuk bekerja dan naik kelas. Sebaliknya sekeras apapun kerja IRT dalam menjalankan “kariernya” sumbangan mereka tak direkognisi dan dinilai secara konkrit.
Secara sosial, biasanya orang akan berharap bahwa reward akan mereka terima dari suami atau anak-anak. Namun ini mengandaikan setiap pasangan mendapatkan penghargaan atas perannya itu dan negara ikut memastikan terjaminnya reward ini. Lalu bagaimana pula dengan IRT yang secara de facto menjadi orang tua tunggal, atau suami tak bertanggung jawab? Sementara penghargaan yang lebih nyata dari negara atas peran dan sumbangsih mereka nyaris tak terdengar.
Sesungguhnya jika negara punya political will untuk menghitung sumbangan mereka, negara akan diuntungkan dengan bertambahnya nilai jumlah tenaga kerja dan sumbangannya. Misalnya dengan menghitung curahan waktu kerja IRT. Dan itu sangat dimungkinkan.
Ketika suami saya mendapatkan pendidikan di Australia dan kemudian di Amerika, para ibu rumah tangga, bahkan untuk keluarga pendatang seperti kami, mendapatkan peluang untuk tumbuh kembang dalam fungsinya sebagai IRT. Mereka direkognisi dan dipenuhi kebutuhannya sesuai perannya sebagai IRT. Mereka dimudahkan untuk bekerja mencari nafkah baik paruh waktu atau penuh sambil tetap berstatus sebagai IRT. Seseorang yang memilih profesi sebagai IRT masih dapat mengembangkan diri karena negara mengakui keberadaan mereka. Berbagai fasilitas yang ramah pada kebutuhan IRT seperti teknologi, industri makanan cepat saji yang sehat dan murah, dan sistim dukungan yang menimbang peran dan kebutuhan IRT tersedia. Tempat penitipan anak yang dilindungi pengawasannya tersedia di mana-mana. Negara juga menyediakan fasilitas antar jemput sekolah serta fasilitas bermain yang aman. Sementara itu di tiap lingkungan ada perpustakaan yang referensinya selalu diperbaharui dan ramah kepada kondisi dan kebutuhan IRT terutama yang membawa anak-anak.
Meskipun hanya kerja sampingan, pendapatan IRT di kedua negara itu dapat mencukupi kebutuhan keluarga muda seperti kami. Ketika pasangannya tak ikut mencari nafkah karena harus menulis disertasi atau harus riset penuh waktu, mereka masih tetap terjamin kesejahteraannya dengan income yang diperoleh IRT. Ini juga karena model dan sistem pengupahan memungkinkan bagi IRT menjadi pekerja sesuai dengan waktu yang mereka punyai yang menggabungkan antara pengurus rumah tangga dan pencari nafkah.
Di Indonesia, setelah kami pulang, dan saya memilih menjadi IRT saya kehilangan fasilitas serupa itu. Kemacetan di kota besar, keterbatasan fasilitas bagi IRT untuk mengembangkan diri dengan biaya murah sulit diperoleh. Selain itu, sistem pengawasan bagi keselamatan anak-anak di ruang publik sangat buruk, demikian halnya pengawasan pada produk makanan di luar rumah. Situasi itu mengharuskan IRT bekerja penuh waktu hanya untuk keluarga. Namun akibatnya, makin menempatkan IRT pada situasi yang tak dikenali peran dan sumbangannya. Kini, mengingat jumlah IRT cukup besar, sudah saatnya negara memiliki kebijakan yang mengakui peran IRT. Dan itu harus berangkat dari kerangka teoretis yang mampu menghidung kehadiran dan sumbangan IRT bagi pembangunan.
—
Penulis merupakan anggota jaringan peneliti Rumah Kita Bersama, dan artikel ini pernah diterbitkan di Harian Kompas dan Rumah KitaB.


 Photo by
Photo by