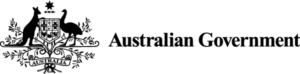Membaca Fikih Perempuan Bekerja dari Kacamata Dr. Muhamad Ali
Tulisan ini diolah berdasarkan hasil diskusi buku Fikih Perempuan Bekerja, 21 Juli 2021
Oleh: Fadilla Putri
Dr. Muhamad Ali merupakan seorang Associate Professor of Religious Studies and Director of Middle East and Islamic Studies Program di University of California, Riverside, Amerika Serikat. Salah satu materi yang beliau ajarkan adalah terkait perempuan dan gender dalam sejarah, dalam agama-agama dan budaya, juga dalam konteks perkembangan gerakan pembebasan dan kesetaraan gender Muslim di Timur Tengah, Barat, dan Indonesia. Dr. Ali sangat mengapresiasi isi buku Fikih Perempuan Bekerja karena topik dalam buku ini sangat penting dan bisa menjadi bahan dan data kajian-kajian empiris bagaimana kenyataan sikap laki-laki dan perempuan terhadap perempuan bekerja di Indonesia. Menurutnya, ini adalah buku pertama yang membahas perempuan bekerja dalam konteks Indonesia. Ada beberapa poin hasil bacaan Dr. Ali, dan beliau fokus di Bab 3 tentang penggunaan maqashid syariah dalam mendukung perempuan bekerja.
Sebelumnya, Dr. Ali menggambarkan bagaimana kajian gender di Amerika. Meskipun kajian ini lebih dulu ada di Amerika daripada Indonesia, tetapi ini bisa berjalan bersamaan dan saling memengaruhi. Kajian-kajian di Amerika bisa memengaruhi di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Artinya, kita masih mempunyai potensi yang luar biasa untuk melahirkan perempuan-perempuan sebagai penafsir. Misal bukunya Ibu Lies Marcoes yang berjudul Merebut Tafsir. Itu adalah salah satu contoh kita membutuhkan penafsir-penafsir baru dalam Islam. Karena di Amerika juga penafsir Islam masih didominasi oleh laki-laki. Beliau berharap buku ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, juga bisa mewarnai gerakan dan wacana kesetaraan gender khususnya perempuan bekerja di Amerika dan Indonesia.
Masalah perempuan bekerja bukan masalah komunitas Muslim saja, melainkan juga di komunitas agama lain. Di Amerika juga ada kajian yang menarik soal public role of women in America dan diskusinya juga mirip; mereka menggunakan teks-teks dan institusi agama yang cenderung patriarkal dan misoginis, karena memang majelis agama yang mengeluarkan aturan keagamannya kebanyakan laki-laki.
Kita biasa menggunakan kata Jahiliah, termasuk juga dalam buku ini. Kita membedakan antara masa Jahiliah dengan masa Islam, seolah-olah masa Islam (masa diturunkannya Al-Qur’an) itu sudah final dan dalam masa Jahiliah posisi semua perempuan kurang baik. Namun, kita perlu membaca juga sejarah pra-Islam. Kalau di dalam buku ini, perempuan sebelum Islam mengalami diskriminasi (tidak bisa bekerja, sulit menginisiasi perceraian, sulit menjadi pemimpin). Namun, dalam buku-buku sejarah pra-Islam, di masa pra-Islam (Jahiliah) banyak juga perempuan mempunyai posisi yang kuat dan mereka bekerja. Contohnya Siti Khadijah, ia bekerja sebelum menikah dengan Nabi Muhammad saw. Pada masa pra-Islam, perempuan yang independen dan mandiri itu sudah ada. Namun memang dominannya masih patriarkal. Tapi jangan mengatakan bahwa seluruh Jahiliah itu tidak memberikan peran perempuan yang setara.
Dulu, sebelum Islam, bukan hanya di Timur Tengah tetapi juga di Yunani, Romawi, Byzantium dan lainnya, sebetulnya mereka juga memiliki praktik yang beragam. Perempuan yang menjadi Nabi, menjadi Tuhan, dan figur Tuhan perempuan (female Goddess) cukup populer di beberapa peradaban sebelum Islam. Namun dalam peradaban Islam, Yahudi, dan Kristen, Tuhan digambarkan laki-laki, dan bahasa teks tentang Tuhan adalah laki-laki.
Selama ini kita kerap menyangka, Barat selalu baik dari pada Timur, begitu juga dalam kesetaraan gender. Nyatanya tidak begitu. Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani, fungsi dan peran perempuan adalah memproduksi keturunan. Artinya, ia masih menganggap perempuan lebih rendah. Ia juga membandingkan bahwa perbandingan antara perempuan dan laki-laki adalah seperti jiwa dan badan, seperti berpikir rasional dan emosional. Hal inilah yang dikritik oleh para feminis di Barat. Mereka mengkritik sejarah yang misoginis, patriarkal, dan anti kesetaraan gender. Hal inilah yang perlu disampaikan pada tokoh agama; ini bukan persoalan Barat, bukan persoalan kita ingin meminjam Barat secara sepenuhnya dan dipaksakan untuk memahami persoalan Islam dan Timur.
Contoh lain tentang pra-Islam yang berkaitan dengan perempuan bekerja adalah, di buku ini ditulis transaksi ekonomi begitu kompleks untuk perempuan. Oleh karenanya, perempuan dianggap tidak pandai mengurus keuangan. Artinya, yang harus mengurus keuangan adalah laki-laki. Pandangan ini muncul dari hukum Athena dan Yunani, yang artinya di Barat pun menghadapi persoalan yang sama. Hal inilah yang kemudian dikritik oleh para feminis di Barat.
Beberapa catatan penting Dr. Ali dari buku Fikih Perempuan Bekerja adalah:
- Teks sebagai nash. Apakah teks seperti arrijalu qawwamuna ‘alannisa itu deskriptif atau preskriptif? Deskriptif itu hanya mendeskripsikan memang pada waktu turunnya ayat itu adalah arrijalu qawwamuna ‘alannisa. Namun kalau preskriptif, maka itu normatif. Kalau memahaminya secara preskriptif, maka laki-laki harus menjadi pemimpin. Memahami deskriptif dan preskriptif adalah dua paradigma yang berbeda. Inti yang secara umum dipahami adalah arrijalu qawwamuna ‘alannisa bukan sekedar khabar, tetapi insya’i. Ini adalah dua perspektif yang bisa saling menguatkan. Meskipun di dalam buku ini, arrijalu bisa jadi adalah perempuan dan rijal bukan berarti perempuan biologis. Makna rijal di dalam buku ini adalah penafsiran yang menarik dan progresif. Penafsiran seperti ini bisa terus dikembangkan.
- Apakah nash termasuk Al-Qur’an itu final atau sebagai proses. Kalau kita melihat Al-Qur’an sebagai final, kita akan sering mentok. Karena bagaimanapun di dalam Al-Qur’an tertulis tentang perbudakan atau tentang poligami. Kalau kita memahami teks sebagai final, perdebatannya akan sangat panjang karena mereka juga akan menganggap hal itu adalah preskriptif. Jadi memahami mana yang prinsipal, fundamental, dan furu’iyyah akan berbeda-beda. Oleh karenanya, muncul kelompok konservatif dan progresif karena teks itu sendiri yang dipahami secara final. Kalau kita menganggap Al-Qur’an sebagai proses, mungkin akan lebih baik. Menurut saya, perlu dikedepankan memahami teks Al-Qur’an (bukan hanya hadis) sebagai proses dan respons pada masa itu.
- Berkaitan dengan maqashid syariah, ada lima hak yang ditulis di buku ini. Maqashid syariah bisa konstruktif dan destruktif. Baik Salafi maupun Islamis juga ada yang menggunakan maqashid syariah untuk melanggengkan ketidaksetaraan gender. Tantangannya adalah bukan antara konservatif dan progresif, tetapi progresif yang Islamis dan progresif non-Islamis.
- Terakhir, tafsir kita masih komunalisme (berpikir tentang komunitas) yang mengandung unsur conformity, yaitu bagaimana meng-conform terhadap yang mayoritas (mainstream). Menurut beliau, salah satu tantangannya adalah bagaimana perempuan diberikan ruang seluas-luasnya untuk memiliki agensi dan memiliki otonomi individual. Boleh saja perempuan itu sebagai pribadi berbeda dari orang lain, termasuk berbeda dari keluarga atau Hal yang dijamin dalam konsep feminis Barat adalah otonomi individual sehingga perempuan menjadi kritis, mandiri, dan bisa menafsirkan ulang teks-teks sesuai dengan apa yang ia rasakan sebagai kebenaran berdasarkan pengalamannya. Karena menurut beliau, maqashid syariah bukan hanya soal proteksi, tetapi persoalan kebebasan.