Bagaimana Kita Bisa Melindungi Perempuan Hamil yang Bekerja Saat Pandemi?
Oleh: Fadilla Putri
Baru-baru ini, sahabat sejak masa kecil mengeluhkan betapa sulitnya harus pergi bekerja di masa pandemi ketika hamil. Saat ini ia memasuki kehamilan trimester keduanya. Keluhan itu bahkan telah ia utarakan sejak awal kehamilannya: tidak bisa makan karena seringkali berujung mual hebat hingga muntah, merasa tidak sehat tapi tak ada penyakit kecuali kehamilan itu, tidak nyaman atau sedih tapi sulit untuk diceritakan atau dikeluhkan karena hal itu dianggap hal yang biasa. Kejadian-kejadian itu kerap ia alami bahkan ketika dekat dengan suaminya, atau di tengah keluarga, atau di kantor.
Pengalaman hamil tentu akan menjadi memori yang sangat lekat bagi perempuan. Ketika saya hamil tiga tahun lalu, saya mengalami masa-masa terberat karena gangguan kehamilan. Saya tidak boleh turun dari tempat tidur karena cenderung mengalami pendarahan. Ketika itu saya masih belum berkantor di Rumah KitaB. Karena keluhan-keluhan itu sekitar tiga minggu saya absen dari kantor. Setelah merasa kuat dan kembali ke kantor, waktu bekerja sering saya habiskan berbaring di dalam ruang menyusui karena saya dilarang dokter duduk dalam jangka waktu lama. Beruntung saat itu saya bekerja di sebuah kantor untuk perlindungan anak, sehingga hak saya sebagai perempuan bekerja yang sedang mengandung sangat dilindungi.
Dalam keadaan dunia yang “normal” pun, kehamilan itu berat. Al-Qur’an surat Lukman ayat 14 disebutkan: “Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”
Al-Qur’an menyebutkan bahwa perempuan hamil berada dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah. Ibu Lies Marcoes, Direktur Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), kerap kali menjelaskannya sebagai “berat di atas berat” dan “sulit di atas sulit” untuk menjelaskan betapa beratnya kehamilan itu.
Sahabat saya ini bekerja di sebuah instansi di bilangan Jakarta. Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan, setiap pekan ia wajib masuk kantor secara bergiliran; satu hari di rumah, satu hari di kantor, begitu seterusnya. Bahkan akhir tahun lalu, ia masuk kantor hampir setiap hari karena banyaknya deadline pekerjaan akhir tahun.
Sebuah riset yang dilakukan oleh dosen Universitas Indonesia, Kanti Pertiwi, pada 96 perempuan pekerja usia 20-50 tahun sepanjang Juni-Agustus 2020 menunjukkan bahwa informan perempuan merasakan tekanan dari kebijakan kantornya yang maskulin selama pandemi. Tolak ukur produktivitas dan beban kerja tidak mengalami penyesuaian meskipun pandemi (sumber).
Selain lansia, orang dengan penyakit penyerta, dan tenaga medis, perempuan hamil termasuk ke dalam kelompok rentan terhadap Covid-19. Kehamilan sendiri sudah mengandung risiko. Ditambah dengan adanya pandemi, seorang perempuan hamil menjadi semakin rentan terhadap Covid-19.
Kebijakan kantor yang tidak sensitif gender menganggap seolah-olah keadaan seorang perempuan hamil adalah sama dengan pekerja lainnya. Ketika perempuan mengalami hambatan bekerja karena kehamilannya, hambatan itu harus ditanggulangi sendiri karena tidak ada upaya untuk memperbaiki atau mengakomodasi kebutuhannya. Muncul juga anggapan perempuan hamil tidak bisa seproduktif kolega lainnya karena “kesalahannya” sendiri atas keadaannya. Perempuan sendirilah yang harus menanggung risiko untuk bisa catch up dengan kolega lainnya. Cara pandang ini telah mengabaikan hak yang paling dasar yang dilindungi baik oleh agama maupun oleh Undang-Undang Kesehatan.
Padahal, adalah kewajiban perusahaan atau instansi terkait untuk melindungi, atau setidaknya mengakomodasi kebutuhan para perempuan hamil yang aktif bekerja.
Pertama, perusahaan bisa memberikan fleksibilitas kepada karyawan atau staf perempuan yang sedang hamil untuk mengurangi jadwal “piket”nya untuk masuk kantor guna meminimalisasi kontak dengan banyak orang tanpa harus mengurangi kewajibannya dalam bekerja. Ini berarti perusahaan atau instansi mengeluarkan kebijakan bahwa perempuan hamil bisa bekerja dari rumah sepanjang kehamilannya. Terutama jika kantor berada pada gedung tertutup yang tidak memungkinkan protokol VDJ yang maksimal (ventilasi, durasi, dan jarak), karena risiko Covid-19 tidak hanya ada pada sang ibu, tetapi juga pada sang bayi. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jelas ditegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, sementara definisi anak adalah seseorang di bawah 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan. Ini artinya, perempuan hamil berhak mendapatkan perlindungan maksimal atas keselamatan janinnya, termasuk oleh perusahaan/instansi tempat ia bekerja, karena haknya dilindungi oleh negara.
Kedua, mengakomodasi kebutuhan perempuan hamil jika ia tetap harus masuk kantor. Memang, tidak semua jenis pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Beberapa pekerjaan, teruma yang berhubungan dengan sektor jasa, membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerjanya. Akan tetapi, banyak cara yang dapat dilakukan untuk melindungi perempuan hamil selama ia bertugas. Misalnya, dengan memberikannya ia akses pada ruangan privat agar dapat beristirahat ketika lelah atau mengalami mual hebat. Dalam keadaan khusus, misalnya ketika kehamilan seorang perempuan mengalami risiko tinggi—entah risiko perdarahan dan lainnya—perusahaan dapat mengurangi beban atau jam kerjanya, atau menggunakan hak cuti sakitnya.
Ketiga, hak perempuan dilindungi dalam pasal 82 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk mendapatkan paid maternity leave selama 3 bulan. Artinya, ia dibayar penuh selama cuti hamil dan melahirkan. Bahkan, beberapa perusahaan di Indonesia telah menerapkan cuti 6 bulan bagi perempuan yang melahirkan untuk mendukung ASI eksklusif.
Masalahnya, tidak semua perusahaan atau tempat kerja memiliki perspektif yang sama. Hasil analisis situasi perempuan bekerja yang dilakukan Rumah KitaB pada Agustus-September 2020 lalu di Bandung misalnya, menemukan sebuah perusahaan yang sama sekali tidak memberikan hak cuti bagi perempuan, baik cuti haid, hamil, maupun melahirkan. Sehingga, para pekerja perempuan yang hamil terpaksa harus mengundurkan diri sebelum melahirkan karena haknya untuk tetap bekerja pasca melahirkan tidak terpenuhi.
Pada akhirnya tulisan ini ingin menekankan bahwa, dalam kondisi dunia yang “normal” pun, kehamilan sudah berat. Bisakah terbayangkah bagaimana beratnya hamil dalam kondisi krisis wabah global? Ini adalah kewajiban perusahaan, lembaga, dan negara untuk melindungi kelompok rentan Covid-19, tak terkecuali perempuan hamil yang bekerja. Kebijakan tempat kerja dan pemimpin perempuan yang memahami pengalaman unik perempuan adalah salah satu kunci untuk mendukung agar perempuan dapat terus berpartisipasi di ruang publik, apapun kondisinya.
—
Penulis merupakan staf di Rumah KitaB dan tulisan ini pertama kali dipublikasikan di sini.


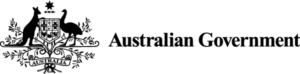




Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!