Ketika Bekerja Bukan Sekadar Pilihan
Oleh: Dinda Shabrina
Narasi keagamaan yang mendorong perempuan untuk tinggal di rumah sebagai “kodrat”nya sepertinya tak memahami realitas perempuan dengan status yang ragam. Sebagai anak, sebagai istri dengan suami menganggur atau sebagai ibu tunggal akibat perceraian atau bahkan sebagai lajang. Narasi-narasi yang menyatakan surga perempuan adalah rumah dan bidadari rumah adalah perempuan jelas tak bisa berlaku bagi semua perempuan. Itu hanyalah sebuah mimpi bagi sebagian perempuan meskipun mereka meyakini dan bahkan menginginkannya.
Sebab bagi sebagian perempuan, hal itu seperti sebuah kemewahan. Tidak semua perempuan memiliki situasi kehidupan yang bisa menggantungkan hidupnya pada orang lain entah itu ayahnya atau suaminya. Tidak semua perempuan bisa dengan hanya melakukan pekerjaan domestik, lalu kebutuhan perutnya terpenuhi.
Narasi-narasi agama yang mendorong perempuan kembali ke rumah luput membaca kenyataan hidup perempuan-perempuan yang kurang beruntung dan terpaksa bekerja di luar rumah demi memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Belum lagi jika perempuan sendiri menghendaki bekerja di luar rumah sebagai aktualisasi diri dan atau menghendaki sebagai ibadah amaliyahnya.
Seorang perempuan remaja yang saya temui di depan Mall Bekasi yang jualan kopi pakai sepeda keliling ketika penelitian kualitatif untuk mengonfirmasi tentang indeks penerimaan perempuan bekerja (Rumah Kitab 2021) menyadarkan saya soal ini. Ikhiari, sebut saja namanya begitu. Ia bercerita apa artinya bekerja bagi dirinya juga orang tuanya.
“Kita terlahir dari keluarga dengan kondisi ekonomi berbeda-beda. Apakah seorang perempuan, anak pedagang kaki lima seperti saya bisa seterusnya menadahkan tangan untuk menerima uang dari orangtua? Apakah ayah saya akan selamanya hidup dan mampu membiayai kebutuhan saya dan Ibu?”
Sebagai pencari nafkah ayah saya tak selamanya sehat dan hidup di dunia. Ia masih punya tanggungan Ibu, saya dan adik. Orang yang berdagang seperti ayah saya di halaman Mall ini juga banyak. Kami sama-sama mengadu nasib. Dagangan ayah kadang juga tidak laku. Ibu saya yang dulu membantu ayah mencari tambahan dengan menjadi tukang cuci untuk kakak-kakak yang kerja di pabrik. Sekarang tidak bisa lagi. Selain pada punya mesin cuci atau nyuci kiloan, kondisi fisiknya juga lemah. Saya, sebagai anak pertama yang mampu secara fisik tentu tidak bisa tinggal diam. Saya tidak mungkin membiarkan ayah saya mencari sendiri untuk menutupi kebutuhan keluarga. Sementara kebutuhan hidup harus terus dipenuhi, bayar token listrik, biaya sekolah adik, biaya pengobatan ibu, dan lainnya. Kalau ngikutin ceramah-ceramah yang bilang surga istri itu di rumah ya siapa juga yang nggak mau? Tapi Ibu saya bagaimana?
Bagaimana dengan nasib perempuan janda, baik ditinggal mati suaminya atau cerai hidup, apakah mungkin bisa terus bergantung pada harta kekayaan suaminya? Itu pun kalau suaminya meninggalkan harta warisan. Kalau tidak?
Seperti kisah hidup Meli, seorang perempuan janda yang saya temui saat melakukan penelitian pertengahan tahun 2020 lalu. Sedari kecil Meli menerima narasi bahwa perempuan “salihah” sebaiknya ada di rumah. Karena memang “kodrat” perempuan yang ia pahami dalam Islam ada di dalam rumah. Mengerjakan pekerjaan domestik, memasak, menyuci, mengurus anak, dll. Ia menerima narasi semacam itu dari lingkungan keluarga, tetangga dan ceramah-ceramah yang pernah ia dengar. Saat remaja pun ia mengimpikan untuk menjadi perempuan sebagaimana yang dinarasikan tadi. Tetapi ternyata beranjak dewasa, kenyataan tak pernah memberinya kesempatan untuk dapat menjadi perempuan “salihah”.
Tamat sekolah, Meli harus menerima kenyataan untuk membantu ayahnya mencari nafkah. Karena adik-adiknya yang harus meneruskan sekolah dan kuliah butuh biaya yang banyak. Ia berpikir mungkin selama menjadi gadis, ia belum bisa menjalani kehidupan sebagai perempuan yang “salihah” dan sesuai “kodrat”nya. Baginya bekerja saat itu semata-mata sebagai bentuk baktinya dengan orangtua. Ia pernah bercerita pada saya bahwa kelak, setelah berumah tangga, ia akan menjadi perempuan salihah yang berdiam di dalam rumah dan mengabdikan diri untuk suaminya.
Namun kenyataan berkehendak lain. Cita-citanya untuk menjadi perempuan salihah setelah menikah pun tidak kesampaian. Ia menikah dengan seorang lelaki bermasalah dan tak setia. Selama menikah yang menjadi pencari nafkah utama adalah Meli. Selama setahun pernikahan, yang Meli tahu, ia dan suaminya hidup berkecukupan. Mereka sama-sama masih bekerja.
Merasa kondisi ekonominya selalu stabil, Meli sempat berencana untuk resigned dari kantornya agar cita-citanya menjadi perempuan salihah itu dapat terwujud. Apalagi saat itu Meli sudah memiliki anak, ia merasa bahwa perannya sebagai seorang ibu, madrasah pertama bagi anak-anaknya dibutuhkan. Tetapi belum sempat Meli mewujudkan niatnya untuk berhenti dari pekerjaan, Meli mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dan selama ini tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Selama ini justru suaminya malah menimbun hutang dimana-mana demi menutupi kebutuhan hidup agar terlihat memiliki pekerjaan tetap. Kenyataan pahit itu harus diterima dan dijalani Meli.
Sebagai seorang perempuan janda dengan dua orang anak, Meli harus menata kembali hidupnya. Ia harus bisa menyulap dirinya untuk menjalani berbagai peran. Menjadi seorang ibu sekaligus bapak, menjadi pekerja, pengurus rumah tangga. Tentu saja itu semua tidak mudah. Lalu apakah Meli lantas menjadi perempuan yang tidak salihah? Dengan rentetan kenyataan hidup yang harus ia jalani, apakah Meli tak pantas masuk surga hanya karena ia masih bekerja di luar rumah demi menghidupi dirinya dan keluarganya?
Akibat dari narasi keagamaan yang Meli terima bahwa perempuan salihah adalah perempuan yang ada di rumah, Meli menjadi khawatir apakah yang ia jalani saat ini diridhoi oleh Allah? Padahal melihat kondisi di rumah tangganya, suami tidak selalu memberi nafkah, tidak punya pekerjaan yang jelas, dan parahnya malah berselingkuh. Apakah Meli lantas diam saja? Sementara kedua anaknya yang butuh makan dan susu.
Perlahan Meli menerima itu semua dan mengubah pandangannya bahwa apa yang dilakukannya kini, perempuan janda yang bekerja di luar rumah, bukanlah sesuatu yang buruk. Sejak Meli bertekad untuk berdiri kembali setelah bercerai, Meli tak sedikitpun meratapi dirinya sebagai janda. Ia justru selalu mendorong dirinya untuk tidak pernah menyerah berjuang melanjutkan hidup. Ia menganggap apa yang dilakukannya saat ini sebagai ladang pahala. Meli tidak lagi merisaukan apakah ada surga untuk dirinya yang bekerja di luar rumah. Ia fokus menciptakan surga seperti yang ia pahami bersama anak-anaknya di rumahnya.
—
Penulis merupakan peneliti Rumah KitaB dan tulisan ini pertama kali dipublikasikan di sini.

 Photo by
Photo by  Photo by
Photo by 
 Photo by
Photo by 
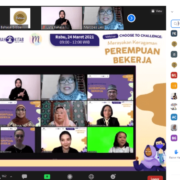
 Photo by
Photo by 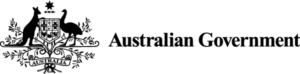

 Photo by
Photo by  Photo by
Photo by 
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!