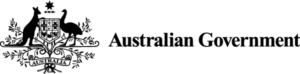Fitnah, Fitrah, dan Kekerasan Berbasis Gender
21 Oktober 2020, Rumah KitaB mempresentasikan penelitiannya tentang fundamentalisme (dalam) Islam dan dampaknya kepada kekerasan berbasis gender. Penelitian satu tahun di lima kota ini menyajikan temuan yang layak timbang untuk merumuskan penanganan kekerasan ekstrem di Indonesia. Empat pertanyaan diajukan dalam penelitian etnografi feminis ini: pandangan tentang perempuan, sosialisasi ajaran, dampak, dan resiliensinya.
Berdasarkan empat pertanyaan penelitian, secara berturut-turut penelitian ini mencatat sejumlah temuan. Pertama soal apa dan siapa perempuan. Melalui hegemoni ajaran, perempuan terus menerus ditekankan sebagai sumber fitnah (keguncangan) di dunia. Kehadirannya, terutama di ruang publik menjadi lantaran instabilitas moral yang (dapat) merusak tatanan sosial bahkan ekonomi. Untuk mengatasi hal itu, perempuan karenanya musti tunduk pada fitrahnya sebagai pihak yang harus dikontrol, diawasi, dicurigai dan batasi hadirnya di ruang publik baik secara langsung maupun simbolik.
“Iman mah kuat, ini si“amin” yang tak kuat. Keluhan personal seorang guru- pemilik si “amin” itu segera menjadi landasan keluarnya regulasi yang kewajiban murid dan guru perempuan (muslimah) memakai jilbab. Ini terjadi di sebuah SMA Negeri di salah satu lokasi penelitian ini. Namun hal sejenis dalam upaya menormalisasikan konsep perempuan sebagai fitnah dapat ditemukan di kelembagaan mana saja hingga perempuan sendiri merasa “salah tempat”.
“Setiap kali mau berangkat kerja, rasanya seperti mau ke tempat maksiat, sejak di jalan, di pabrik sampai pulang saya terus ikhtilat [bercampur dengan bukan muhrim]”. Keluhan seorang buruh perempuan yang telah berpakaian rapat ini akhirnya berujung pada “pilihan” mundur dari dunia kerja.
Kedua, ajaran serupa itu disosialisasikan dan dinormalisasikan lewat ragam cara. Cara konvensional seperti ceramah:
“Biar nangis darah, Bu, fitrah wanita mah tidak mungkin bisa sama dengan laki-laki, pertama wanita tak bisa sempurna ibadahnya karena ditakdirkan haid, nifas, perempuan suka ghibah (gosip), suka riya (pamer) suka tabarruj (dandan); kedua Allah sudah mengunci, sudah menetapkan laki-laki adalah pemimpin atas perempuan.
Ceramah lain di tempat lain begini ujarnya:
“Allah telah menetapkan kepala keluarga itu laki-laki, pencari nafkah itu laki-laki. Bagi yang tidak ada suami, yang jomblo, sama saja. Mereka tanggungan Bapaknya, atau walinya […] Namun Barat telah mengubahnya [..] Wanita sekarang ikut mengejar karier, anak dan rumah ditinggal. Laki-laki kehilangan martabatnya. Aturan Allah laki-laki memimpin, jelas itu, tapi ikut-ikutan [Barat], perempuan jadi manajer, jadi direktur, laki-laki jadi bawahan, hasilnya apa? Ketika ada pelecehan, minta Undang-Undang KDRT, UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kan lucu…, kalian yang tak nutup aurat, kalian yang nggak mau di rumah, pas kena resikonya kalian nyalahin laki-laki”.
Sosialisasi dan normalisasi ajaran perempuan sebagai fitnah ini gencar bukan main. Ini dilakukan melalui ragam platform sosial media serta kampanye kreatif lainnya. Dalam 13 minggu, peneliti di suatu wilayah, misalnya peneliti mencatat ada 23 flyer yang menyebarkan ajakan perempuan berhijrah.
Ketiga, ajaran dan ujaran yang disampaikan terus menerus setiap hari itu mampu membobol mental mereka. Mereka cemas, takut, merasa tidak aman oleh sebuah hidden power yang terus menggedor kesadaran mereka bahwa mereka memang ditakdirkan sebagai suluh neraka. Pengecualiannya adalah jika mereka pasrah ikhlas pada apapun yang didapat dari suami sebagai imamnya.
“Benar, suami adalah pencari nafkah, itu wajib. Tapi kalau ibu-ibu ikhlas atas apapun pemberian suami, tidak ngomel, tidak melawan, tidak maido (mencela), jannah menanti ibu dari mananpun pintu masuknya”.
Namun pelanggengan ajaran dan ujaran ini tak terjadi tanpa kuasa atas modal dan pasar.
“Mau jilbab Dewi Sandra, atau hijab Umi Pipik, atau Peggy Melati Sukma Umi jual, dulu juga jual kerudung bordir model Ibu Gus Dur, tapi sekarang nggak laku lagi, lagian kan nggak syar’i, pakai kerudung tapi leher kelihatan, mana bisa, makanya nggak laku saya juga nggak jual lagi.”
“Aurat perempuan ya aurat, mau bayi mau dewasa, barangnya itu-itu juga. Laki-laki banyak juga yang kegoda lihat aurat bayi perempuan. Jadi bukan asal jualan, kita jualan untuk dakwah, menghindari setan masuk ke pikiran, biar nggak terjadi zina, minimal ndak zina mata.”
Adopsi terhadap pandangan serupa ini juga nggak recehan. Mengikuti keyakinan bahwa tempat terbaik perempuan adalah di rumah, para subyek penelitian ”menerima” pembatasan ruang gerak ekonomi dan sosialnya.
Sebagian besar, terutama kaum pendatang, seperti para pekerja urban, mengalami keterputusan dengan akar tradisinya karena ajaran [baru] yang mereka ikuti telah memutus mewajibkan untuk seluruh keterhubungan mereka dengan kampung (tradisi beragama, tradisi budaya, cara berpakaian, cara berkeluarga dan cara bersilaturahmi) dengan alasan untuk menghindari perbuatan dosa besar dari bid’ah. Hal ini memunculkan ketergantungan mereka kepada kelompok-kelompok barunya di kota yang diikat oleh keyakinan-keyakinan baru mereka dalam ragam kelompok seperti salafi. Seorang mantan buruh di Bekasi mengurai kegelisahannya.
“Kadang saya kangen pulang ke Jawa, tapi di kampung tidak ada yang pakai hijab begini, Ibu saya karena belum paham juga tidak setuju saya pakai baju ini. Maklum ibu saya petani. Lebaran tahun lalu tersiksa rasanya karena banyak yang nggak ngaji sunah. Wara wiri tetangga saudara-saudara naik motor kreditan, isi rumah mebel baru kreditan. Padahal itu semuanya hasil riba, haram. Badan saya rasanya panas.”
Namun penelitian ini juga mencatat ragam perlawanan perempuan meskipun tidak/ belum membentuk agensi. Paling jauh berupa adaptasi terhadap perubahan- perubahan itu, atau perlawanan tanpa kekuatan pengorganisasian dan apalagi sikap kritis. Sebagian bahkan ”melawan” karena tak punya kesanggupan untuk ikut hijrah akibat kemiskinananya.
Demikianlah kekerasan ekstrem yang terpetakan dalam penelitian itu. Ini hanya dapat bisa dibaca dengan kaca mata yang peka dan sanggup membaca bagaimana perempuan dibentuk dan didefinisikan. Sistem patriarki telah melanggengkan kuasa laki-laki terhadap perempuan melalui kontrol, dan kepemilikan yang distrukturkan oleh ideologi dan sistem keyakinan. Padahal kontrol, kuasa, dan kepemilikan itu sangat rentan memunculkan kekerasan; fisik non-fisik serta hal-hal yang diakibatkan oleh sistem dominasi dan struktur yang menghasilkan ketidaksetaraan.
Situasi ini semakin gayeng karena pasar dan modal ikut melanggengkannya melalui konsep barang dan jasa serba syar’i. Namun, sikap negara yang seolah menarik jarak dari campur tangan terhadap masuk dan berkembangnya pandangan ekstrem serupa ini, telah melanggengkan kekerasan terhadap perempuan melalui hegemoni nilai-nilai patriarki yang terkandung dalam tafsir dan praktik keagamaan fundamentalis.
Hal ini jelas tak bisa terus berlangsung. Karenanya, penelitian ini merekomendasikan hal-hal yang seyogyanya dilakukan negara, masyarakat sipil, pelaku usaha utamanya para pendukung Islam moderat Indonesia secara lebih luas. Mewujudkan human security yang komprehensif dengan menggunakan perspektif gender yang mengharuskan tersedianya sistem perlindungan (protection) sekaligus pemberdayaan (empowerment) akibat cuci otak fitnah dan fitrah.

 Photo by
Photo by