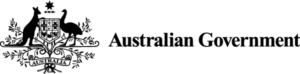Oleh: Wa Ode Zainab ZT
Perempuan identik dengan pekerja domestik, suatu perkerjaan yang secara stereotype dikaitkan dengan ‘dapur, sumur, dan kasur’. Walaupun aktif dalam ranah publik, perempuan tidak dapat keluar dari lingkaran tersebut. Anehnya, pekerjaan di ruang publik dianggap sebagai pilihan yang bisa dilakukan oleh lelaki atau perempuan, namun untuk pekerjaan domestik seluruh norma moral, sosial, bahkan politik menetapkannya sebagai kewajiban perempuan.
Tulisan ini menguraikan ragam elemen konstruksi gender yang mengikat perempuan pada kewajiban kerja-kerja domestik serta implikasinya, dan kemungkinan untuk membongkarnya dengan membahas ulang norma gender perempuan bekerja
Saya melihat fenomena terikatnya perempuan pada dua jenis pekerjaan itu saat masih kecil pada diri Bunda (Ibu kandung saya). Sebelum subuh, Bunda mengurus pekerjaan domestik, termasuk menyiapkan keperluan anak-anak dan suaminya. Setelah semuanya selesai, Bunda berangkat kerja. Sore hari setelah pulang tidak membuatnya bisa beristirahat. Bunda dihadapkan kembali dengan setumpuk pekerjaan rumah dan pelayanan terhadap keluarganya.
Ayah saya bukan lelaki yang merupakan salah satu orang yang hidup dalam konstruk sosial-budaya yang beranggapan bahwa pekerjaan domestik memang tugas perempuan. Berdasarkan pengalaman itu, maka Bunda mengingatkan agar membuat kesepakatan dengan pasangan sebelum menikah. Termasuk di dalamnya, berkaitan dengan pembagian peran domestik dan mewujudkan cita-cita.
Saat saya melanjutkan kuliah dan bekerja, Bunda membantu mengasuh anak kami. Suami pun sangat mendukung keputusan tersebut karena sudah disepakati bersama. Dengan kerelaan hatinya, suami ikut-serta mengerjakan pekerjaan domestik yang dulu asing baginya. Sehingga, dalam rumah tangga kami, suami dan istri sama-sama mengerjakan tugas domestik dan publik.
Memutus Mata Rantai Beban Ganda
Masing-masing perempuan bekerja memiliki berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi, tuntutan zaman, atau eksistensi dirinya sebagai manusia untuk mengaktualisasikan potensinya. Namun, struktur sosio-kultural yang menganut sistem patriarki mengakibatkan perempuan bekerja rangkap dan mengalami beban ganda.
Menurut kamus Keluarga Berencana, double burden (beban ganda) berarti perbedaan perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dengan memberikan pekerjaan lebih banyak (berganda) dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Dalam hal ini, yang dimaksud ialah pihak perempuan diberi beban pekerjaan domestik, namun tak secara otomatis terbebas dari tanggung jawab mencari nafkah, yang secara normatif menjadi tanggung jawab lelaki. Beban ganda ini tidak akan menjadi problematis apabila pola relasi dalam keluarga berbasis prinsip kesalingan atau kemitraan.
Peran ganda disebutkan dengan konsep dualisme kultural, yakni adanya konsep domestic sphere dan public sphere Beban ganda adalah partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu ,dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat, dan manusia pembangunan. (Keppi Sukesi, 1991).
Tantangan Dilematis
Akibat konstruksi gender dalam masyarakat patriarki yang berpusat kepada lelaki, perempuan kerap menghadapi tantangan di dalam dirinya, tempat kerja, maupun di masyarakat. Perempuan terkadang memandang rendah dirinya sendiri, sehingga tidak memiliki bargaining, misalnya apabila membicarakan soal kenaikan gaji atau posisi. Perempuan acap kali ‘pasrah’ menerima segala ketentuan perusahaan atau institusi. Jika laki-laki memperjuangkan hal itu dianggap suatu kewajaran karena terkait perannya sebagai pencari nafkah utama sementara perempuan dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, ta peduli kenyataannya di mana lebih dari 72% perempuan mencari nafkah untuk dirinya dan 4 orang anggota keluarganya terlepas dari apapun status perkawinannya (Yooke Schreves, 1988).
Perempuan juga harus menghadapi tantangan di tempat kerja. Seringkali mereka dianggap tak memiliki kecakapan cukup sehingga harus membuktikannya lebih baik dari yang lain (lelaki). Secara psikologis ketika berada di posisi menengah bukan top leader, perempuan seperti harus bersaing dengan perempuan lain, bukan ‘partner kerja’, karena sulitnya menggapai posisi tinggi. Dan hal yang paling berat, perempuan menghadapi situasi kerja yang tidak aman, rentan kekerasan, atau disingkirkan.
Sebagaimana dilaporkan LBH Jakarta, tahun 2016, Serikat Buruh yang tergabung dalam Pokja Buruh Perempuan yang terdiri dari 80 perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung melaporkan, minimal ada empat jenis kekerasan yang kerap dialami perempuan bekerja (buruh pabrik). Pertama, kekerasan seksual, seperti mengomentari bentuk tubuh atau cara berpakaian buruh perempuan, dipaksa kencan oleh atasan, bahkan diperkosa.
Kedua, kasus kekerasan fisik, seperti dipukul, dijewer, dicubit, dilempar benda keras, dan digebrak meja. Ketiga, kekerasan verbal, misalnya diancam atau diintimidasi akan diadukan atau diputus kontrak dengan kata-kata kasar, menakut-nakuti, menghina, dan memaki. Keempat, Pelanggaran terhadap hak maternitas, seperti keguguran di tempat kerja yang dianggap bukan kecelakaan kerja, tidak ada fasilitas ruang laktasi, sulitnya cuti haid, serta tidak adanya tunjangan bagi buruh yang hamil dan melahirkan.
Tantangan lainnya, perempuan bekerja mendapatkan upah yang minim atau lebih rendah dari pekerja laki-laki. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Mei 2019, rata-rata upah laki-laki sebesar Rp. 3,05 juta sedangkan perempuan sebesar Rp. 2,33 juta. Senada, sebuah laporan pada 2017 dari Australia Indonesia Partnership for Economic Governance menemukan bahwa perempuan Indonesia hanya dibayar 70-80% dari apa yang diperoleh laki-laki per jam-nya.
Menurut Lies Marcoes, Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), berbagai tantangan yang dihadapi perempuan bekerja lahir dari pandangan yang tidak konsisten dalam mendukung perempuan di ruang publik; terkadang didukung karena perempuan secara stereotype dianggap pekerja yang taat, sabar dan bisa dibayar murah, terkadang ditolak, paling cepat dirumahkan jika terjadi pengurangan pekerja dengan asumsi mereka pencari nafkah tambahan. Kedua situasi ini seringkali menggunakan argumen norma gender yang berasal dar pandangan keagamaan.
Konsistensi Dukungan
Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai beban ganda ialah pembagian tugas yang jelas. Ini dimaksudkan agar fungsi keluarga tidak terganggu karena akan mempengaruhi sistem yang lebih besar. Jadi, alih-alih menyelesaikan akar persoalannya, banyak kelompok agama yang menegaskan agar perempuan tetap tinggal di rumah.
Dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menegaskan kewajiban bekerja yang berlaku bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti ayat ini: “Jika kamu selesai shalat, segeralah bertebaran di muka bumi untuk mencari anugrah Allah dan sering-seringlah mengingat Allah supaya kamu beruntung” (QS. Al Jumu’ah: 10). Selain itu, Dr. Abd al-Qadir Manshur, seorang ulama dalam Buku Pintar Fikih Wanita, menyebutkan banyak teks hadis dan pendapat ulama yang menyebutkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja, baik sebelum atau sesudah menikah.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis, seperti Imam Ahmad, Imam Ibnu Sa’d, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Baihaqi. Istri Abdullah bin Mas’ud, Rithah, datang menemui Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, saya perempuan pekerja, saya menjual hasil pekerjaan saya. Saya melakukan ini karena saya, suami saya, dan anak saya tidak memiliki harta apapun”. Kemudian Rasulullah pun merespons: “Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka.”
Pada realitasnya, kita tidak bisa menafikkan fenomena perempuan bekerja. Namun sayangnya, perempuan bekerja dihimpit oleh dua belah pihak. Di satu sisi, kapitalisme yang hanya mengeksploitasi perempuan; di lain sisi, struktur sosial budaya yang tak mendukung perempuan bekerja. Sehingga, kesetaraan gender sudah sepatutnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari karena bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga merupakan pondasi yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.
—
Penulis merupakan peneliti di Rumah KitaB.


 Photo by
Photo by  https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peasants_breaking_bread.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peasants_breaking_bread.jpg
 https://riaupos.co/thumb/2813-81-kar.jpg
https://riaupos.co/thumb/2813-81-kar.jpg https://prod.smassets.net/assets/cms/cc/uploads/int_womens_day-2.jpg
https://prod.smassets.net/assets/cms/cc/uploads/int_womens_day-2.jpg
 Naya Cheyenne
Naya Cheyenne